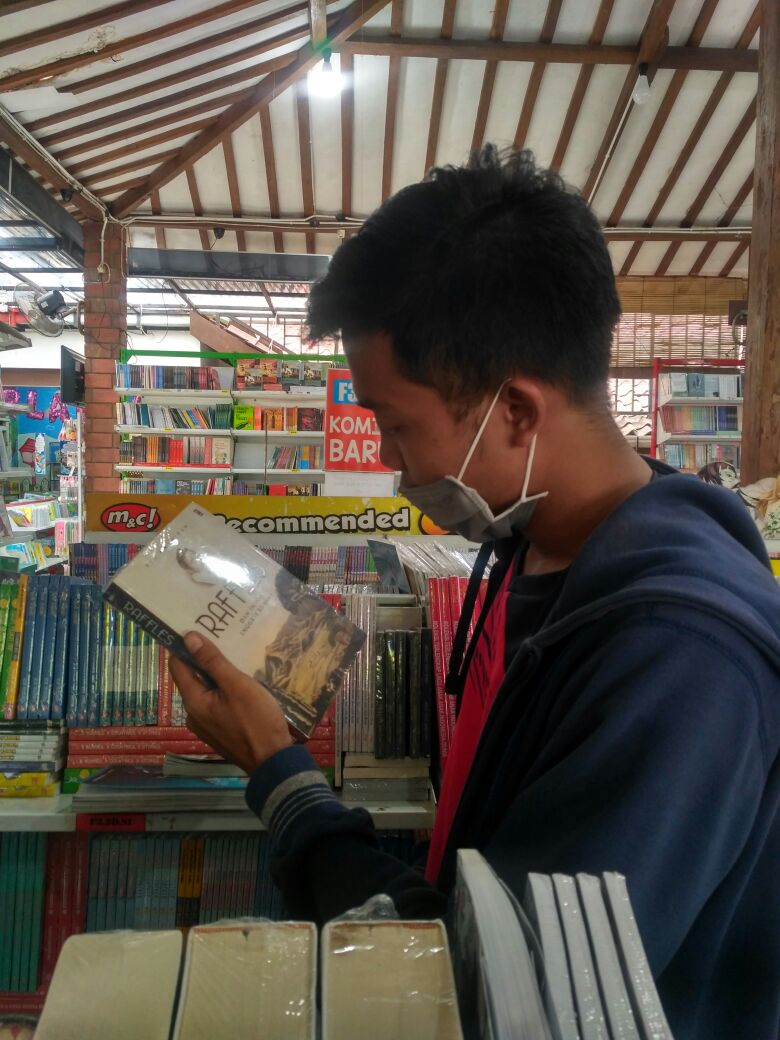|
| Manusia Perahu Etnis Rohingya |
Sabtu, 31 Desember 2016
Holocaust Etnis Rohingya
Isu Rohingya kembali viral dan menjadi perbincangan hangat di penghujung tahun ini. Dimulai ketika pembunuhan sembilan penjaga perbatasan di Rakhine Utara (Myanmar) oleh kelompok militan Islam Rohingya pada 09 Oktober 2016, dan ditambah dengan perusakan tiga pos keamanan di wilayah yang sama dan oleh kelompok yang sama. Sehingga tragedi itu membuat militer Myanmar dan otoritas pemerintah “amarah” dan melakukan tindakan-tindakan abnormal, keji, kotor, bahkan genderang pembersihan etnis (ethnic cleansing) Rohingya kian ditabuh-kencang. Inilah holocaust (penghancuran/genosida) yang tidak bisa dilupakan begitu saja.
Berbicara holocaust mengingatkan kita pada tragedi Nazi Jerman pada Perang Dunia II, ketika sang komandan Adolf Hitler beserta militernya membunuh jutaan kaum Yahudi dengan tanpa ampun. Pembasmian massal manusia tidak hanya itu saja, holocaust pada akhir abad ke-20 juga pernah menimpa jutaan penduduk sipil di Kamboja oleh Khmer Merah maupun Bosnia oleh Ultra Nasionalis Serbia serta suku Tutsi dan Hutu oleh Interahamwe di Rwanda. Bahkan, dalam dekade pertama abad ke-21, peristiwa serupa kembali terjadi dan menimpa Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar.
Jauh sebelum meletus isu Rohingya tahun 2012, sebenarnya etnis Rohingya telah mengalami diskriminasi masif selama puluhan tahun, baik oleh negara maupun etnis mayoritas yang kebetulan beragama Buddha. Sebelum Burma merdeka pada 1942, ternyata sudah ada benih-benih kekerasan terhadap etnis Rohingya walaupun tensinya lebih rendah. Hingga Burma merdeka holocaust terhadap etnis Rohingya di negeri pagoda itu terus berlanjut hingga sekarang. Puncaknya pada bulan oktober-November 2016, terjadi pembantaian etnis Rohingnya untuk kesekian kalinya, dan mengakibatkan 100 korban meninggal, 3.000 anak mengalami malnutrisi, puluhan perempuan diperkosa, dan 1.200 bangunan dibakar. Maka tak ayal, mereka berbondong-bondong hengkang dari negara asal, tanpa tujuan yang jelas, tanpa perbekalan cukup, dan nekat mengarungi samudera walaupun ujungnya maut yang mereka temukan.
Abstain
Holocaust etnis Rohingya oleh militer dan mayoritas umat Buddha Myanmar sejatinya melanggar Statuta Roma pada 1998 tentang International Criminal Court (ICC). Dimana holocaust ala Myanmar dalam bentuk state violence (negara melakukan genosida) ethnic cleansing (pembersihan etnis) maupun kejahatan terhadap kemanusian itu adalah pelanggaran HAM berat, baik secara kumulatif maupun alternatif.
Namun otoritas Myanmar berdalih bahwa “mereka bukan warga negara kita, dan kita tidak mengenal mereka”. Hal ini diperparah ketika masyarakat internasional mengecam, justru Myanmar menunjukkan Undang-undang Kewarganegaraan pada tahun 1982, yang isinya sangat rasial, dan menyudutkan Rohingya. Kemudian pada tahun 2012 otoritas Myanmar menegaskan kembali bahwa Rohingya tidak boleh menjadi warga negara Myanmar. Sehingga mereka tidak mempunyai negara (stateless).
Bahkan masyarakat internasional tambah bingung, ketika state couselor (Perdana Menteri) Aung San Suu Kyi tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah terpilih sebagai Perdana Menteri Myanmar pada 06 April 2016, sebetulnya banyak harapan dan pencerahan dipundaknya, terutama bagi etnis Rohingya. Tetapi sebaliknya, Suu Kyi abstain dan mencari tempat aman di bawah bayang-bayang statusnya sebagai peraih nobel perdamain pada tahun 1991 itu. Apalah arti nobel bagi Suu Kyi? Inilah yang harus dipertanyakan manakala ia tetap melakukan pembiaran terhadap tragedi kemanusian yang menimpa negaranya.
Ketika ribuan pengungsi Rohingya semakin membeludak di kawasan Asia Tenggara seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Lagi-lagi Organisasi ASEAN juga tutup mata terhadap tragedi itu, prinsip non-intervensi yang diusung ASEAN terlalu mengekangnya untuk berbuat sesuatu, sehingga ASEAN juga memilih abstain dan memasrahkan kepada setiap negara anggotanya yang tengah berkonflik. Tapi yang perlu diingat masyarakat ASEAN itu satu tubuh, ketika salah satu organ tubuh sakit maka harus dipahami nyerinya akan dirasakan ke organ tubuh lainnya. Jika ASEAN tetap demikian, maka benar yang dikatakan Suargana Pringganu “Masyarakat ASEAN akan seperti raksasa berjalan di dalam lumpur”.
Proaktif dan Pasif
Melihat tragedi holocaust etnis Myanmar, sebenarnya ada baiknya pihak penengah menggunakan pendekatan yang didengungkan Dinna Wisnu, yakni dengan proaktif dan pasif, dan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Pertama, menggunakan cara proaktif, suatu negara yang mencoba jadi penengah atas isu Rohingya akan dituntut secara gigih menggali informasi dari Myanmar tentang dimensi-dimensi masalah kekerasan di Rakhine (Arakan), termasuk juga mengukur besaran konflik untuk kemudian dapat disulkan secara bilateral solusinya. Tapi harus diingat negara penengah harus dapat menjamin bahwa kekerasan tidak akan berlanjut. Cara proaktif bisa tetap diplomatis, tidak konfrontatif dan tidak memalukan Myanmar.
Pendekatan kedua menggunakan cara pasif, negara penengah akan dituntut lebih banyak wait and see, bicara dengan otoritas Myanmar tetapi cenderung fokus pada aspek yang ditawarkan Myanmar saja, dengan harapan agar tiap langkah negera penengah tidak disalahartikan. Pendekatan pasif ini tergolong aman baik dari segi persepsi, sumber daya, maupun perencanaan. Namun kekurangannya adalah tidak mustahil korban masih akan terus berjatuhan dan yang tidak sabar akan menggunakan isu ini sebagai amunisi untuk menuding ketidakberdayaan negara dalam melindungi muslim di Myanmar. Dari kedua pendekatan ini, naifnya mayoritas negara ASEAN memilih cara kedua. Selain dirasa aman dan karena susahnya mendekati Myanmar, mereka lupa jutaan etnis Rohingya masih terkatung-katung di lautan dan ketika sampai pesisir mereka malah diusir.
Prahara di Langit Desember
Berada di ujung tahun laksana berada di atas bukit. Dari atas bukit akan terbentang cakrawala maha luas, eksotis, dan tak terbatas. Dari atas bukit mata diberi kesempatan melihat pelbagai panorama, dan kesempatan melihat ke dalam diri tentang perasaan nelangsa yang membayangi masa lalu, masa kini, dan masa depan manusia.
Berada di ujung tahun adalah memparadekan debar jiwa. Dimana sebagian kita kadang terjebak pada gerbong hura-hura, sengaja mewarnai langit dengan kembang api, membisingi ruang dan waktu dengan suara leking terompet, dan kadangkala muda-mudi (mohon maaf) melucuti keperawanannya demi satu malam yang katanya sakral itu. Demi malam itu sebagian kita berharap semburat fajar kebaharuan yang telah lama lucut dari adabnya. Dan menghunjamkan spirit “kelahiran kembali” yang lahir dari kesadaran baru.
”Lahir” sebagai simbol terlepasnya diri dari sekapan kegelapan, dari keyakinan menikung yang tak membawa pencerahan dan dari gelegak nafsu yang dapat menjungkalkan marwah kemanusiaan ke tubir kehinaan. Dan ”baru” sebagai metafora kehidupan dengan semangat yang berbeda dari sesuatu yang kita anggap ”lama”.
Lebih luas lagi, seperti didengungkan Bang Asep Salahudin bahwa ”baru” itu satu tubuh dengan kebudayaan yang berjangkar pada etos penciptaan kebeningan batin (Cicero), keluhuran nalar (Raymond Williams), kekukuhan menjunjung tinggi nilai universal (Kant), daya imajinasi kreatif (Schiller), terus mengupayakan terwujudnya masyarakat sempurna (EB Taylor) melalui gelegak daya kehidupan dengan membiarkan insting natural menemukan katupnya yang optimal (Nietzsche).
Ketika berada di ujung tahun, sepatutnya dijadikan momentum meraih pembebasan, meneguhkan sikap keterbukaan dan penegasan posisi dari keberagamaan dan kebernegaraan kita. Karena bagaimanapun kita akan mengkonstruksi konsep diri kita dengan mengendarai waktu. Ini barangkali yang jadi alasan metafisis, dalam ajaran Islam, Tuhan banyak bersumpah menggunakan diksi yang berdimensi waktu. Sebut saja: demi masa (wal ashri), demi malam (wal laili), demi siang (wan nahari), demi fajar (wal fajri), demi bulan (wal qamari), demi matahari (wasy syamsi), demi waktu duha (wadh dhuha).
Hasan al-Basri menambahkan tentang prahara waktu, “Hai anak Adam, sesungguhnya hidup kamu adalah himpunan hari-hari. Setiap hari milikmu itu pergi, berarti pergilah jua sebagian darimu”.
Tapi kadang kita terperangkap pada kata “waktu”. Kata “waktu” akan menjadi antitesis ketika dikawinkan dengan “baru”, keduanya memiliki ruas dan rel masing-masing dan tak bisa disatu-ranjangkan. Waktu tak pernah mengalami kebaharuan meskipun hari, bulan, tahun, dan abad telah berguguran. Waktu berjalan linear: melesat cepat ke depan menembus berbagai zaman meski penghuni semesta ini telah ribuan kali berganti dan berguguran. Bersama kecepatan pula kemudian sejumlah imperatif kehidupan hilang. Sehingga pada titik nadir ini, untuk apa mengucapkan “selamat tinggal Desember” dan “selamat datang Januari”.
Barangkali kita akan sedikit merasa tertusuk-tusuk untuk tidak melakukan lelaku mubazir di ujung tahun ketika membaca sajak Nota Bulan Desember karya Penyair Ahmad Nurullah: Tak perlu kuucapkan “selamat tinggal” pada detik terakhir bulan Desember / dan “selamat datang” untuk detik awal Januari / Untuk apa? Segala waktu sama / Waktu adalah sumbu semua sejarah, ibu segala kepedihan. Almanak pun jatuh. Telungkup. Tahun bersalin / Tapi, di antara detik-detik yang gugur, bulan-bulan membusuk / hari-hari berkarat, dan jam yang menguning, banyak hal yang masih lengket—berkecamuk dalam kenangan.
Bahkan di bait ketiga dan keempat Nurullah seakan memparodikan keputusasaannya akan makhluk yang bernama waktu itu. Seperti almanak yang tajuh ia gambarkan tentang egoisnya waktu yang melibas beberapa peristiwa dan tragedi. Dalam konteks negeri ini misalnya, ketika waktu mempertontonkan tanah meledak, kota-kota terbakar, AIDS, flu burung, demam berdarah, busung lapar, fluktuasi BBM, harga-harga menjerat leher. Atau dalam rentang 12 bulan tahun 2016 misalnya, ditemukan isu bom dan terorisme, LGBT, reshuffle Kabinet, banjir Garut dan Bima, korupsi, pembakaran tempat ibadah, aksi demonstrasi 411 dan 212, pesona kopi Jesicca, bahkan berita nahas kegalaan Timnas Garuda mengangkat Piala AFF untuk yang kelima kalinya.
Sedangkan dalam konteks lintas batas garis teritorial, kita jumpai tragedi holocaust etnis Rohingya di Myanmar, ISIS di Irak dan Suriah, gelombang pengungsi Timur Tengah yang membanjiri Eropa, Brexit (British Exit), konflik Bashar al-Assad dengan oposisi, konflik Syiah-Sunni, bom di Turki, terpilihnya Antonio Gutteres sebagai Sekjen PBB, mangkatnya Raja Thailand Bhumibol Adulyadej, mangkatnya Komandan Fidel Castro, dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat yang diluar dugaan melenggang mulus menyingkirkan Hilary Clinton. Tapi waktu tak peduli. Waktu terus berjalan, mengusung detak-detaknya, diam-diam menyembunyikan wajahnya di balik paras bulan merekah. Waktu adalah siluman yang pandai menyamar.
Lalu apa yang baru dari waktu? Apa yang hendak kita rayakan pada tahun baru?. Dengan nada dan getar yang sama, atau bahkan lebih lirih lagi Nurullah kembali membatin: Seperti waktu, akupun terus berjalan: gelisah oleh tatapan / mata bulan. Gemetar di bawah kerling matahari / sebab, gara-gara waktu, banyak hal berdesak untuk diingat / dan aku berjuang untuk lupa—sebagai jalan / pembebasanku.
Maka diujung tahun ini, dengan tanpa niatan menyakiti penyuka gemerlap malam pergantian tahun. Alangkah etis dan beradabnya kita menyerobot kopi ditemani sebungkos rokok saja di rumah, atau duduk di kursi goyang sambil mendengarkan lagu Auld Lang Syne karya Robert Burns (penyair Skotlandia), yang liriknya berkisah tentang persahabatan, persaudaraan, dan menyiratkan pentingnya mengenang dan merenungkan peristiwa yang sudah-sudah.
Jumat, 16 Desember 2016
Ekologi Sastra di Bantaran Sungai
Peradaban dunia banyak dibangun dari peradaban sungai. Sungai menjadi ikon penting, yang diyakini manusia—dari pelbagai lini masa—sebagai sarana kelangsungan kehidupan, dan mengantarkannya pada gelanggang kemajuan yang sakral. Peradaban suatu bangsa/kelompok yang masyhur ialah menjaga ekosistem sungai pada koridornya agar tetap lestari. Sehingga ekologi antara makhluk dan lingkungan tetap harmonis.
Melihat sungai adalah melihat sejarah. Banyak negeri yang masyhur karena mencipta peradabannya melalui sungai: seperti Mesir dengan Lembah Sungai Nil-nya, atau Mesopotamia yang bergantung pada Sungai Eufrat dan Tigris, India dengan Sungai Indus dan Sungai Gangga, China dengan Sungai Huang Ho (Kuning), dan tentang keangkeran Sungai Amazon di Amerika Selatan. Semuanya memiliki khazanah dan sejarahnya masing-masing. Bahkan, Sungai Nil (Mesir) oleh seorang ahli sejarah Yunani, Heredotus mengatakan “tanpa Sungai Nil Mesir tidak mungkin maju, Mesir adalah hadiah sungai Nil.”
Melihat sungai adalah melihat sejarah. Banyak negeri yang masyhur karena mencipta peradabannya melalui sungai: seperti Mesir dengan Lembah Sungai Nil-nya, atau Mesopotamia yang bergantung pada Sungai Eufrat dan Tigris, India dengan Sungai Indus dan Sungai Gangga, China dengan Sungai Huang Ho (Kuning), dan tentang keangkeran Sungai Amazon di Amerika Selatan. Semuanya memiliki khazanah dan sejarahnya masing-masing. Bahkan, Sungai Nil (Mesir) oleh seorang ahli sejarah Yunani, Heredotus mengatakan “tanpa Sungai Nil Mesir tidak mungkin maju, Mesir adalah hadiah sungai Nil.”
Kamis, 15 Desember 2016
Tiket Masuk Surga
 Berbicara tentang surga, tentu dalam konteks hari ini tidak mubazir untuk diperdebatkan. Karena keagungan yang dimilikinya, serta menjadi orientasi final manusia dan menjadikan surga sebagai impian untuk lekas mendapatkannya. Surga tempat makhluk Allah dan orang-orang mukmin yang mengagugkan Allah akan hidup kekal dan abadi di sana.
Berbicara tentang surga, tentu dalam konteks hari ini tidak mubazir untuk diperdebatkan. Karena keagungan yang dimilikinya, serta menjadi orientasi final manusia dan menjadikan surga sebagai impian untuk lekas mendapatkannya. Surga tempat makhluk Allah dan orang-orang mukmin yang mengagugkan Allah akan hidup kekal dan abadi di sana.Mafhum dipahami, di surga tidak ada malapetaka, lelah, sakit, luka, lesu, penat, bosan, malas, lapar, haus, dan sebagainya. Di sana hanya ada kesenangan, kemudahan, dan keindahan. Istana di dalam surga terbuat dari emas. Bebatuannya terbuat dari mutiara, zabarjad (batu mulia), dan yakut (permata). Pepohonannya tidak bisa dijelaskan karena kebaikan dan keindahannya.
Di sana juga terdapat buah-buahan yang enak, segar yang beragam. Di sana juga terdapat banyak burung keberuntungan yang senantiasa memanggil orang-orang muslim sejati ketika menginginkan dan mengharapkan sesuatu, tanpa meminta dan tidak perlu dan mengharapkan sesuatu, tanpa meminta dan tidak perlu memeras pikiran atau berjuang. Itu merupakan dambaan dan kenyataan, permohonan dan pelaksanaan.
Mengenai Saya
Popular Posts
-
Google.com Sang Comandante Fidel Alejandro Castro Ruz, telah meninggal dunia pada jumat (25/11) pukul 10:30 malam waktu setempat. Kuba ...
-
Masih lekat dalam ingatan saya ketika mengikuti dialog sirkus sastra Salihara 11 Maret 2014, waktu itu Penyair Sapardi Joko Damono d...
-
Puisi adalah sebuah karya fiksi yang begitu mistik untuk dicerna, bahasanya yang puitik, kata-katanya yang efektif, dan pengandaiann...