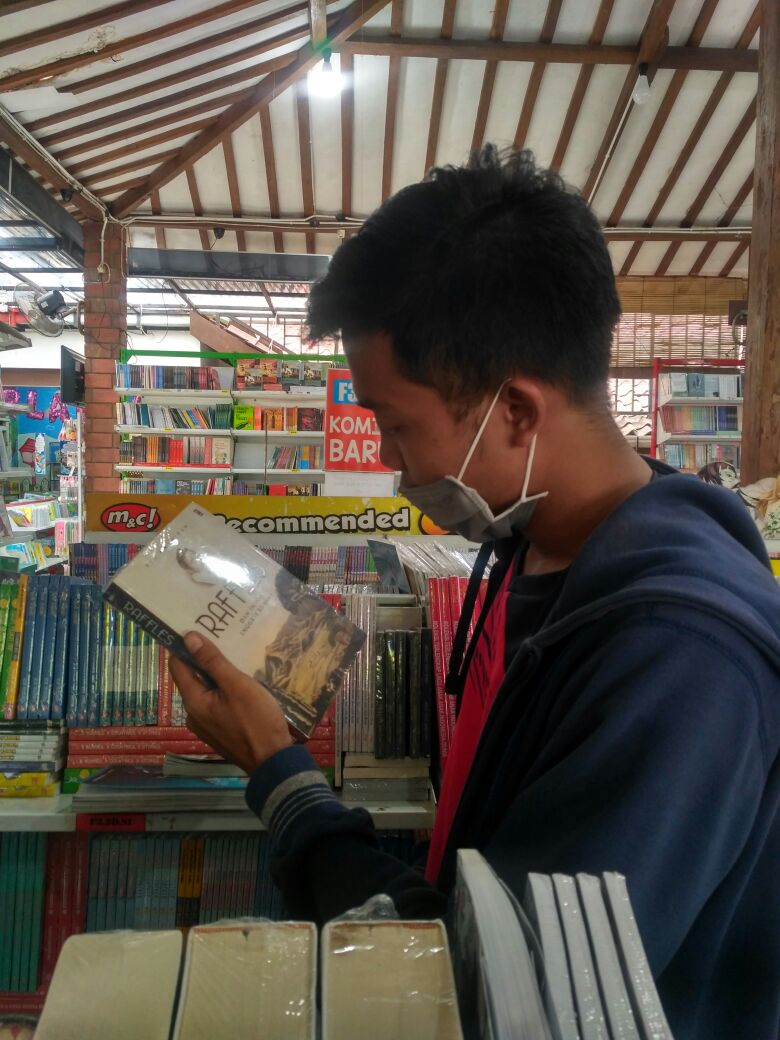Jumat, 27 Januari 2017
Widji Tukul, dan Oase di Padang Kesusastraan
Kesusastraan kita tengah menggeliat di awal tahun ini. Bukan karena hibrida sastrawan muda, atau jutaan antologi puisi, cerpen, dan novel ramai dibedah, tapi karena pemutaran film biopic Wiji Thukul, Istirahatlah Kata-Kata. Film gubahan Yosep Anggi Noen (2016) ini tayang serentak di bioskop jaringan XXI di 19 kota di seluruh Indonesia, pada tanggal 19 Januari, dan untuk mengenang 19 tahun hilangnya Wiji Thukul (1998). Angka 19 sengaja dipakai sebagai simposium duka kolektif bangsa ini, atau usaha merawat ingatan dan menolak tegas upaya melupa tragedi penghilangan Wiji Thukul beserta 12 temannya.
Malam itu, orang berbondong-bondong memadati bioskop dari berbagai latar berbeda-beda. Selain berpijak pada penasaran, ada juga kalangan yang pernah berlintasan dengan Wiji dalam paruh hidupnya, pegiat HAM, akademisi, politikus, sastrawan, bahkan kelompok-kelompok arus bawah yang nasibnya paralel dengan Wiji Thukul ikut dalam kemanunggalan emosi yang sama. Maka tak ayal di semesta maya ramai Tagar #ThukulDiBioskop dan #IstirahatlahKataKata dan begitu banyak foto lembaran tiket diposting. Hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya animo penonton belum jua surut.
Laki-laki kelahiran Solo, dan tidak fasih menyebut huruf (r) itu memang eksentrik. Bayangkan saja, di Semarang penonton tak beranjak hingga layar disimpulkan. Di Surabaya, sejumlah anak muda berdiri dan melantunkan “Darah Juang” sebelum memasuki studio. Di Medan, kerumunan orang tak juga berakhir kendati bioskop telah ditutup. Buku saku berisi puisi Wiji dibagikan kepada penonton. Poster film jadi rebutan untuk berfoto dan dipajang. Ruang-ruang diskusi yang menurut produsernya menjadi spirit awal terciptanya film ini kembali terbuka. Hingga dipungkasi dengan fenomena nostalgik di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Setelah nonton film Wiji akan dilanjutkan dengan “Ngamen Puisi.” Istilah “Ngamen Puisi” memang sangat lekat dengan aktivitas Wiji, di masanya ia memang rajin menggelar acara pembacaan puisi dari kota ke kota, yang ia beri nama sendiri “Ngamen Puisi.”
Sang buruh pabrik itu laiknya magnet. Pada tubuhnya yang ringkih berdiam nyali, pada kakinya yang jenjang berdaki meluap-luap energi yang tak mau diam, pada lidahnya yang pelo berbiak api, kata-kata Wiji dalam sebaran puisi-puisinya adalah api yang membakar semangat buruh dan pembangkang, hingga membikin junta militer Soeharto ketar-ketir (Muhidin M Dahlan, 19/01/17).
Pemutaran film Istirahatlah Kata-Kata banyak menuai simpati, walaupun di sana-sini masih banyak yang mencibir. Tapi presentase sementara menunjuk akan tingginya simpati, bukan karena kasus penghilangan Wiji, atau karena keadilan sulit ditegakkan, tapi karena Wiji berhasil menghidupkan puisi dan sifat bengalnya ke ruang publik, dengan medium yang tak biasa.
Jalan kepenyairan Wiji memang penuh duri dan tebing yang curam. Dengan latar yang bukan apa-apa ia bisa menggegerkan otoritas pemerintah saat itu, bahkan hingga kini gejolak apinya masih membara disaat keadilan kian terpasung. Dengan medium kata-kata ia mampu menampar siapa saja yang tidak memihak kepada penghuni arus bawah. Coba simak puisinya yang begitu menohok ini: Seumpama bunga/ Kami adalah bunga yang tak/ Kau hendaki tumbuh/ Engkau lebih suka membangun/ Rumah dan merampas tanah/ Seumpama bunga/ Kami adalah bunga yang tak/ Kau kehendaki adanya/ Engkau lebih suka membangun/ Jalan raya dan pagar besi (Puisi, Bunga dan Tembok).
Puisi Wiji seolah menghantui kaum elit yang doyan menggorok kaum pinggiran. Seolah teori Dependensia (ketergantungan), kelompok Periphery (pinggiran) terbiasa menggantung kepada Center (Pusat) tidak laku lagi di hadapan Wiji. Wiji Thukul dan puisinya memangkas sekat itu untuk pembiasaan tidak diam, untuk tidak menjadi bunga yang selalu dirontokkan. Tapi menjadi bunga matahari meskipun tumbuhnya di kolong jembatan tapi sinarnya mampu menerangi jalanan di atas jembatan.
Gejolak api perlawanan dengan medium puisi memang ampuh, bahkan memasyarakatkan puisi dengan ditayangkan ke bioskop-bioskop ketika bangsa ini terasing dengan dunia literatur juga begitu menjanjikan. Kita masih ingat ketika muda-mudi atau kaum uzur sekalipun tiba-tiba belepotan kata-kata romantis setelah menonton film AADC 2 (2016). Aan Mansyur sebagai orang yang bertanggungjawab, karena puisinya dibacakan Rangga untuk Cinta itu luar biasa romantis, penuh dengan metafor dan diksi mendayu-dayu dan mampu menghasut orang-orang yang awam puisi tiba-tiba menulis puisi.
Dunia kesusastraan kita kalau dikatakan stagnan, tidak juga. Dikatakan maju, ternyata tak. Kesusastraan kita memang bisa melangkah tapi geraknya seperti kura-kura atau siput yang lamban sekali geraknya. Karena kesusastraan wabil khusus puisi seolah berada pada ruang sunyi yang tentu orang-orang pilihan saja yang bisa memasukinya. Industri buku puisi pun beberapa tahun belakangan tampak lesu dan tak menumbuhkan minat baca publik. Penyair mati bila dihadapkan dengan penjualan buku puisi yang selalu sepi di bawah oplah minuman dan makanan ringan. Penyair lebih memilih mempublikasikan puisi-puisinya melalui media massa dan kemudian membukukan secara indie atau perorangan.
Maka film AADC 2 banyak ditonton orang, buku tidak ada New York Hari ini pun laris manis dan naik cetak ulang. Sastra seolah menemukan danau di padang yang gersang, sastra seolah menemukan gairahnya sendiri, penyair pun memiliki keyakinan kembali bahwa puisi bukan sekadar nyanyian sepi tanpa pendengar.
Padahal jika merunut sejarah kesusastraan kita ke belakang, puisi sempat menjadi taji tajam yang menguak sisi luka kehidupan sekaligus corong protes cukup nyaring dahulu kala. Bulu kuduk kita berdiri ketika membaca puisi Chairil Anwar, dada kita berdebar ketika nada-nada protes Wiji Thukul dipanggungkan.
Film ternyata bisa menjadi media kampanye paling efektif. Film AADC 2 dan Istirahatlah Kata-kata secara langsung telah menjadi media promosi akan kesususastraan, buku-buku puisi, ajakan kepada setiap kalangan untuk kembali menggandrungi sastra, dan mengetahui sepenggal kisah penyair, cerpenis, dan novelisnya.
Dan yang paling penting film telah membuktikan bahwa perjuangan lewat kata-kata adalah perjuangan yang nyata. Jika Harry Belafonte mengatakan “Anda dapat mengurung penyanyinya, tapi tidak dengan nyanyiannya.” Maka film dan AADC 2 dan Istirahatlah Kata-Kata seolah ingin mengatakan hal yang sama, namun dalam konteks yang sedikit berbeda. Lebih jauh lagi “Anda dapat menghilangkan sang penyair, tapi tidak dengan puisinya.”
Rabu, 18 Januari 2017
Prahara Babat Giyanti
Untuk kesempatan ini Sri Wintala Achmad menelusuri sejarah Babat Tanah Giyanti. Babat yang berisi kisah, perang, dan sketsa kehidupan tiga kerajaan besar (Surakarta, Yogyakarta, dan Praja Mangkunegaran). Ini Suatu laku luar biasa bagi Sri Wintala Achmad, karena untuk menyuntuki sejarah Nusantara tempo dulu (wabil khusus Pulau Jawa) ia akan menemukan duri-duri di setiap perjalanannya. Selain karena kejelimetan dan sulitnya mencari data-data, seorang sejarawan atau penulis sejarah harus berperang dengan waktu dan kehidupan saat yang serba instan.
Dalam buku setebal tiga ratus halaman ini, kita akan dibawa untuk mengingat nama, tempat hari, tanggal, tahun, dan gejolak perang antarkerajaan yang begitu menegangkan. Di bagian awal buku ini mendiskripsikan tentang perselisihan Pangeran Mangkubumi dengan Tumenggung Martapura dan Pangeran Mangkunagara. Perang Sulawesi III, Palihan Nagari, dan beberapa hal tentang kecamuk kerajaan-kerajaan di pulau Jawa. Di bagian tengah buku ini menarasikan dengan detail isi Babat Giyanti, kisah dalam Babat Giyanti dan perjanjian Salatiga. Dan dibagian akhir berisi tentang suasana Surakarta setelah Palihan Nagari, Yogyakarta pasca Palihan Nagari, dan Praja Mangkunegaran pasca Palihan Nagari.
Babat Giyanti adalah sebuah syair dalam bentuk tembang macapat yang dikarang oleh Yasadipura tentang sejarah pembagian Jawa pada 13 Februari 1755. Sesudah keraton dipindahkan ke Surakarta dari Kartasura karena dibakar oleh orang Tionghoa, maka Pangeran Mangkubumi pun keluar dari keraton dan marah sampai memberontak. Sebab tanah bengkoknya dikurangi banyak sekali. Maka berperanglah dia melawan keraton Surakarta. Selama peperangan ini dia dibantu oleh banyak pangeran dan bangsawan lainnya, antara lain Pangeran Samber-Nyawa (Mangkunegara I). Lalu Pangeran Samber Nyawa dibuat panglima perang.
Babad Giyanti membahas peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di pulau Jawa antara tahun 1741 dan 1757. Peristiwa-peristiwa ini ditulis menurut sudut pandang atau opini Yasadipura. Tahun 1746 merupakan sebuah lembaran hitam dalam sejarah Jawa. Sampai tahun 1746 wilayah Kasunanan Mataram mencakup seluruh bagian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun tersebut Mataram secara sekaligus kehilangan seluruh pesisir utara, dan bahkan di antara Pasuruan dan Banyuwangi semuanya hilang. Pada waktu yang sama muncul perang baru lagi di mana Mataram kehilangan separuh daerah yang masih ada. Lalu ketika perjanjian perdamaian ditanda tangani sembilan tahun kemudian, pada tahun 1755, paling tidak separuh penduduk Jawa tewas.
Alasan langsung bencana-bencana ini ialah kunjungan audiensi kepada Susuhunan yang dilakukan oleh Gubernur-Jenderal Van Imhoff pada tahun 1746. Beberapa tahun sebelumnya pesisir utara dan Jawa bagian timur dijanjikan kepada VOC, karena VOC telah membantu Sunan menumpas pemberontakan. Sekarang ini Van Imhoff menuntut janji sang Sunan. Sunan Pakubuwana II yang kala itu menjabat memang pernah menjanjikan daerah-daerah ini ketika ia sedang terjepit. Kala itu dia harus melarikan diri dari keraton sementara dikawal oleh para serdadu VOC (hal. 51-52).
Sunan Pakubuwana II memang tidak banyak mengenal damai dalam masa pemerintahannnya (1726-1749). Warga Tionghoa yang memberontak dan mengacau, karena alasan yang sangat berbeda dan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Sunan yaitu karena ada pembantaian warga Tionghoa di Batavia pada tahun 1740, dan sebuah pemberontakan di Madura yang menjalar ke Jawa Timur. Selain itu di ibu kota sendiri, banyak pangeran-pangeran, “warisan” ayahnya yang memberontak meminta kekuasaan serta intrik-intrik keraton. Salah seorang pangeran yang banyak mengganggu sunan Pakubuwana II adalah kakaknya sendiri, pangeran Mangkunagara. Untungnya Pakubuwana II bisa membuangnya ke Sri Lanka berkat bantuan VOC. Namun bagi putranya, Raden Mas Said, hal ini menjadikan alasan untuk membangkang dan membalas dendam terhadap pamannya, Sunan Pakubuwana II. Karena Pakubuwana II tidak kuat melawan Raden Mas Said, maka dia menjanjikan imbalan bagi yang bisa mengusirnya. Seorang adik Pakubuwana II yang lain, pangeran Mangkubumi berhasil mengusir Raden Mas Said. Namun kemudian patih Sunan Pakubuwana II berpendapat bahwa imbalannya terlalu besar, padahal Sunan Pakubuwana II sebenarnya tidak apa-apa.
Masalah dengan Mangkubumi ini justru terjadi ketika Van Imhoff sedang meminta audiensi di keraton pada tahun 1746. Van Imhoff sebenarnya bersedia untuk membantu Sunan Pakubuwana II, maka diapun menegur Mangkubumi mengenai tuntutannya yang keterlaluan di tempat umum. Lalu Sunan Pakubuwana II memotong imbalannya sampai dua pertiga. Mangkubumi kehilangan mukanya dan tidak bisa tetap tinggal di keraton. Iapun pergi dan mencari kontak dengan Raden Mas Said, keponakannya yang telah diusirnya. Kehilangan muka Mangkubumi sebenarnya bukan satu-satunya alasan, meski alasan utama, menjauhnya Pakubuwana II dengan Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi sebenarnya juga kurang setuju terhadap keputusan kakaknya menyerahkan daerah pesisir dan akan kompensasi VOC yang telah diberikan untuk pendapatan yang hilang.
Perang awalnya berlangsung buruk bagi sunan Pakubuwana II dan sekutunya, VOC. Mereka hanya bisa mempertahankan posisi mereka saja. Musuh mereka menyerang di seluruh pulau Jawa. Bahkan kota Surakartapun tidak aman. Mangkubumi menerapkan taktik perang gerilya.
Sementara ini Mangkubumi tujuannya tidak hanya membalas dendam saja, namun diapun ingin menjadi Sunan. Ketika Sunan Pakubuwana II pada saat berlangsungnya perang jatuh sakit dan mangkat pada tahun 1749, maka Mangkubumi memproklamasikan dirinya sebagai Susuhunan yang baru dan mendirikan keraton di Yogyakarta. Karena Surakarta dan VOC tidak mengakuinya, namun menobatkan putra Sunan Pakubuwana II menjadi Sunan Pakubuwana II, maka kala itu terdapat dua Susuhunan di Jawa.
Kala itu terlihat jelas bahwa kedua kubu tidak ada yang lebih kuat untuk mengalahkan yang lain. Maka kedua kubupun sadar dengan hal ini. Selain itu Gubernur-Jenderal Van Imhoff meninggal pada tahun 1750 dan digantikan oleh Jacob Mossel. Lalu Pangeran Mangkubumi sudah tidak akrab lagi dengan Raden Mas Said sehingga situasipun berubah. Raden Mas Said sendiri memiliki aspirasi untuk menjadi raja. Pada tahun 1754 mulailah rundingan antara Mangkubumi dengan VOC (tanpa melibatkan Raden Mas Said dan Sunan Pakubuwana III). Tawaran Mangkubumi untuk melawan Raden Mas Said, diterima oleh VOC dengan imbalan separuh wilayah kekuasaan Mataram yang masih ada. Tawarannya diterima oleh VOC tetapi kekuatan mangkubumi tidak cukup untuk mengalahkan mas Said. Pada tanggal 13 Februari 1755 perjanjian ini ditanda tangani di desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Mangkubumi akhirnya mendapatkan gelar Sultan Hamengkubuwana I. Sunan Pakubuwana III tidak bisa berbuat lain daripada menerima kenyataan. Sementara itu Raden Mas Said dua tahun kemudian pada tahun 1757 memutuskan untuk menghentikan peperangan dengan syarat dia boleh menjadi raja. Tuntutannya dituluskan dan dia mendapat wilayah yang diambil dari wilayah Surakarta dan diperbolehkan menyebut dirinya Pangeran Adipati.
Judul Buku : Babat Giyanti (Palihan Nagari dan Perjanjian Salatiga)
Penulis : Sri Wintala Achmad
Cetakan : I, Septermber 2016
Penerbit : Araska
ISBN : 978-602-300-293-1
Tebal Halaman: 300
Jumat, 13 Januari 2017
Obituari Januari
 |
| Sumber Gambar: cremationsolutions.com |
Entah mengapa di awal perjumpaan tahun 2017, kita disuguhi begitu banyak manusia-manusia pilihan berpulang menghadap-Nya. Selain jutaan masyarakat sipil meninggal di Timur Tengah akibat gejolak perang, ada barisan tokoh negara, jurnalis, wirausahawan, aktor politik, sampai pemain sepakbola mewarnai langit Januari.
Dari tokoh negara sekaliber Akbar Hashemi Rafsanjani (Presiden ke-4 Iran), sang jurnalis Perang Dunia II (Clare Hollingworth), Kepala Dinas Perhubungan DIY (Sigit Haryanta), sampai Penjawa gawang Arema Malang (Achmad Kurniawan).
Semua almarhum di atas sekarang rekreasi ke surga, dan kesempatan itu datang tiba-tiba, tanpa dinyana dan diprediksi sebelumnya. Seperti angin berhembus, maut pun bisa saja tiba-tiba menghampiri kita yang tengah baca buku dan minum kopi di beranda rumah.
Memang presiden ke-4 Iran, Rafsanjani sudah uzur, meninggal dunia ketika usianya 83 tahun, melebihi puncak umur manusia kejamakan. Ia tidak berdaya menarik napas lagi di rumah sakit Teheran, akibat serang jantung. Kalau melihat geliat hidupnya, memang Rafsanjani tidak pernah merasa renta meskipun jutaan kali orang mengingatkan untuk gantung almamater dari dunia politik. Tahun 2005, ia mencalon diri presiden lagi, setelah dua periode berstatus presiden Iran (1989-1997). Udara politik Iran tidak sesejuk tahun 1989, akhirnya ia kalah dari Mahmoud Ahmadinejad, rival terberatnya dari kubu Aliansi Pembangunan Islam Iran (Alliance of Builders of Islamic Iran). Semasa jadi presiden, prestasi puncaknya adalah mengantarkan Iran lebih terbuka dan membawa Iran bangkit dari trauma berat akibat perang Iran-Irak (1980-1988). Ia pun ikut andil dalam merevolusi Iran bersama Imam besar Khomeini. Rafsanjani meninggal hari Minggu (08/01/2017).
Dari barisan jurnalis, ada nama Clare Hollingworth seorang banal dan pemberani asal Inggris. Meskipun ia meninggal di Hongkong, tapi masyarakat internasional tidak menolak lupa akan aksi heroiknya dalam memburu berita. Ia manusia pertama kali yang mengabarkan awal Perang Dunia II tahun 1939, ketika usinya masih 27 tahun dengan status wartawan pemula. Hollingworth juga jadi juru liput perang mengerikan di Vietnam, Aljazair, Timur Tengah, India, Pakistan, dan revolusi kebudayaan Tiongkok. Pada bulan Agustus (1939) ia sendirian ke perbatasan Jerman-Polandia meliput perang. Di sanalah ia menjadi saksi mobilisasi tank-tank Nazi pimpinan Hitler yang digunakan untuk menginvasi Polandia. Apa saja yang disaksikannya waktu itu, ia tuliskan dalam kolom pertamanya di The Telegraph. Hollingworth meninggal dunia pada usia ke-105 tahun, Selasa 10 Januari 2017.
Dari dalam negeri ada kabar duka menyelimuti Kotamadya Yogyakarta. Sigit Haryanta—sang pengurus transportasi itu—tewas setelah ditabrak sepeda motor di Simpang Tiga Pedes, Argomulyo, Sedayu, Bantul. Bukan mengendarai mobil mewah, juga bukan Motor Gede laiknya Ustad Jefry, ia hanya mengayuh sepeda dari Wates hendak ke Kota Jogja. Jalanan memang kejam, tak ada jaminan status sosial di sana, semuanya rata, sepipih aspal yang kadang mengabarkan kematian bagi siapa pun dan kapan pun. Sehingga kematian tragis itu melahirkan simpati kolektif dari berbagai kalangan, tagar #SepedaSunyi oleh pegiat sepeda Jogja di dunia maya salah satunya. Haryanta sempat dirawat di RSUD Sarjito, tapi akhirnya maut lebih trengginas dari jarum suntik, akhirnya ia menghembuskan napas terakhir, pada hari Selasa 10 Januari 2017.
Selain kabar baik tentang perekrutan pelatih Timnas Indonesia yang baru, Luis Fernandez dan Luis Milla, ada kabar duka menyelimuti jagat persepakbolaan kita. Ahmad Kurniawan atau masyhur di panggil “AK47” mangkat pada hari Selasa (10/01/2017). Ia adalah kakak kandung Kurnia Mega Hermansyah Kiper Timnas Indonesia yang menepis tendangan pinalti pemain Thailand di laga Final AFF pada penghujung Desember 2016. Kepergian Ahmad menyisakkan duka mendalam kerena ia termasuk penjaga gawang tangguh dan hebat untuk ukuran postur tubuhnya yang tidak terlalu tinggi itu. Ada yang unik dari panggilan “AK47”, mengingatkan kita pada merek senapan serbu buatan Rusia, yang menjadi andalan Rusia dalam projek kenegaraannya. Untuk menghormati kepergian Ahmad, pihak klub Kota Apel itu akan mengabadikan nomor punggung 47, tak ada lagi pemain yang akan mengenakan nomor punggung itu. Ahmad meninggalkan satu istri dan dua anaknya yang baru berusia 12 dan 10 tahun.
Kematian memang misteri, semesteri kehidupan manusia yang selalu disibukkan oleh sesuatu yang pada akhirnya tidak menjamin apa-apa. Peristiwa kematian memulai misterinya ketika ada orang mati disandingkan dengan track record selama hidupnya.
Dalam pandangan filsafat Taoisme; hidup dan mati adalah qi yang berkumpul dan buyar, setiap kehidupan dan kematian adalah siklus pergerakan qi. Di dalam qi hidup dan mati itu satu tubuh, hidup sebagai tulang punggung, mati sebagai tulang ekor. Han Feizi (dari mahzab Legalis) membenarkan “hidup adalah perjalanan dan kematian adalah kembali”
Pandangan masyarakat Jawa paralel dengan dengan Han Feizi, kematian bukan peralihan status baru bagi orang mati. Segala status yang disandang semasa hidup ditelanjangi digantikan dengan citra kehidupan luhur. Dalam hal ini makna kematian bagi orang Jawa memacu kepada pengertian kembali ke asal mula keberadaan (sangkan paraning dumadi). Kematian dalam budaya Jawa atau Islam secara khusus selalu dilakukan acara ritual oleh yang ditinggal mati. Setelah orang meninggal biasanya disertai upacara doa, sesaji, pembagian warisan, pelunasan hitang dan sebagainya (Layungkuning, 2013: 98-99).
Hingga di puncak ini, tak ada kata lain “bersiaplah untuk mati”. Segala yang berjiwa akan mati, di mana saja kita berada berita kematian ada di pundak kita.
Rabu, 11 Januari 2017
Rafsanjani dan Fenomena Iran
 |
| Rafsanjani |
Republik rakyat Iran kehilangan sang penyeimbang, Akbar Hashemi Rafsanjani meninggal dunia di Teheran pada hari Minggu 08 Januari 2017. Presiden ke-4 Iran itu menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit karena menderita serangan jantung, pada usia ke 82 tahun. Banyak kalangan merasa kehilangan karena sentuhan revolusionernya.
Akbar Hashemi Rafsanjani atau familiar dengan nama Hashemi Bahramani adalah seorang penulis masyhur dan seorang politisi andal. Ia tokoh utama dibalik berakhirnya dualisme kepemimpinan atau kekuasaan di Iran, dan merupakan salah satu pilar Revolusi Iran (Jomhouri-e Iran) tahun 1979. Sikap pembaharu dalam jiwanya telah tertanam semenjak menduduki jabatan di parlemen sebagai ketua serta komandan pasukan tentara Iran, dan menjadi orang kepercayaan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ruhollah Khomeini.
Ketika masih hidup ia pernah menjabat sebagai Presiden Iran selama dua periode (1989-1997). Sebagai veteran politik, semangatnya tidak pernah padam, bahkan ia mencalonkan diri kembali sebagai Presiden Iran pada tahun 2005, namun dikalahkan Mahmoud Ahmadinejad. Majalah Forbes pernah mencamtumkan Rafsanjani dalam daftar orang terkaya di dunia dan pernah menulis bahwa dialah kekuatan yang sesungguhnya di balik pemerintahan Iran selama 24 tahun terakhir ini.
Dogma Pragmatisme
Kalau flashback lagi ketika Rafsanjani terpilih jadi Presiden Iran pada tahun 1989, hakikanya adalah sebuah keniscayaan, karena pada tahun yang sama Rakyat Iran kehilangan tokoh sentral Imam Khomeini yang meninggal dunia pada tanggal 03/Juni/1989. Rafsanjani seolah menjadi penyeimbang karena kepergian Khomeini membuat Rakyat Iran seperti kehilangan arah, dan menyebabkan banyak benturan kepentingan yang menyelimuti langit Iran. Selain semangat “Khomeinisme” masih menguat, waktu itu juga terjadi benturan antarulama yang berbeda haluan, ditambah persaingan antartokoh dan kelompok yang berbeda secara ideologis.
Begitu Rafsanjani terpilih sebagai presiden, dan Ali Khamenei menjadi pengganti Khomeini, menguatlah persaingan antarfraksi konservatif, pragmatis, dan radikal. Kubu ulama pragmatis berada di bawah Rafsanjani. Visi besar Rafsanjani adalah menciptakan negara yang kuat dengan birokrasi yang mumpuni: mampu dan cakap. Iran akan berfokus untuk membangun kembali masyarakat yang tercabik-cabik dan menyembuhkan luka akibat delapan tahun perang Iran-Irak (1980-1988).
Di bawah masinis Rafsanjani, lokomotif Iran memasuki zaman baru. Masa perubahan yang antara lain ditandai oleh adanya “pergeseran orientasi” dari jagat revolusi ke semesta pembangunan. Ia bahkan mengambil langkah moderasi dalam beberapa kebijakan luar negerinya. “jika orang percaya bahwa kita dapat hidup di balik pintu yang tertutup, mereka itu salah. Walaupun kita harus independen secara pantas, kita membutuhkan kawan dan sekutu di seluruh dunia,” katanya.
Konstelasi politik di dalam negeri pun lebih kondusif untuk gagasan-gagasan reformasi Rafsanjani. Kendati Rafsanjani sering disebut sebagai tokoh “pragmatis dan moderat”, tetapi semakin lama ia memerintah, dukungan cukup kuat dari sejumlah tokoh “garis keras” pun ia dapatkan. Di antaranya adalah, bekas PM Mie Hussein Musawi yang menjadi penasehat presiden urusan politik; Menteri dalam Negeri Hujjatul-Islam Abdullah Nuri; Jaksa Agung Mohammad Khatami (M. Riza Sihbudi, 1991: 225).
Di badan legislatif dan yudikatif, Rafsanjani juga mempunyai pendukung yang cukup besar. ketua Mahkamah Agung Ayatullah Mohammad Yazdi, misalnya, dikenal sebagai pendukung kuatnya. Baik dari yuridis-formal maupun realitas politik; Rafsanjani mempunyai basis kekuasaan yang sulit untuk digoyahkan.
Dalam menyampaikan pidato pelantikannya, Rafsanjani menegaskan bahwa kemerdekaan hanya akan mempunyai arti nyata apabila Iran kuat secara ekonomi. Ia menambahkan “kita tidak bisa membangun bendungan hanya dengan slogan”.
Rafsanjani tampaknya tidak ingin membuang-buang waktu. Sebuah rencana pembangun repelita yang bertujuan memulihkan ekonomi dalam negeri segera disusun. “revolusi adalah tugas revolusioner seluruh bangsa Iran”, kata Rafsanjani. Menyadari betapa parahnya kerusakan Iran akibat perang, ia lebih memprioritaskan program kerjanya pada pemulihan sektor industri, khususnya industri minyak.
Bahkan Rafsanjani memberikan tempat kepada sektor swasta. Ia mengendurkan kontrol sosial: perempuan bebas memilih model kerudung dan menggunakan make up di depan publik, kaum muda lak-laki dan perempuan lebih bebas berbaur di depan umum, pelarangan musik yang diterapkan di zaman revolusi dikendurkan. Pada masa itu, larangan penerbitan buku dicabut, termasuk produksi film dan pertunjukkan teater (The Atlantic, 8/1).
Pukulan bagi Rouhani
Meninggalnya Rafsanjani adalah pukulan telak bagi Hassan Rouhani (Presiden Iran sekarang), karena Rouhani sulit melepaskan pengaruh Rafsanjani dalam roda pemerintahannya, apalagi ia diprediksikan bakal mencalonkan diri sebagai presiden kembali pada Mei 2017. Dalam pemerintahannya selama ini Rouhani banyak mendapatkan dukungan dari Rafsanjani. Bahkan orang mau bekerja dengan Rouhani karena ada Rafsanjani di belakangnya.
Dalam suatu kesempatan Rouhani pernah mengatakan “Rafsanjani adalah legenda keimanan, kesabaran, toleransi dan moderasi”. Sehingga meninggalnya Rafsanjani akan menyulitkan Rouhani dalam sisa-sisa masa jabatannya, kalaupun mencalonkan kembali jadi Presiden Iran belum tentu ia menang karena kalangan reformis mulai memainkan tangan-tangan politiknya.
Dialah “sheikh moderasi”. Selain tokoh lintas negara merasa kehilangan, kepergiannya adalah simposium duka-lara terbesar bagi kubu pragmatis dan kubu reformis Iran saat ini.
Sabtu, 07 Januari 2017
Sinyalemen Aksi Teror pada Awal Tahun 2017
 |
| Sumber Gambar: kabaroke.com |
Pada penghujung tahun 2016, Densus 88 Antiteror Mabes Polri berhasil menembak mati dua orang terduga teroris di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Bahkan dalam waktu hampir bersamaan, sel teror ISIS juga ingin meledakkan Istana Negara (11/12/2016). Beruntung aksi teror itu tercium oleh Densus 88, kalau tidak betapa banyak korban akan berjatuhan. Ini menjadi sinyalemen buruk, bahwa di negeri ini aksi teror masih ada dan mengancam keberbangsaan dan kebernegaraan kita.
Jauh sebelum itu, pada penghujung tahun 2015, Zaenal ditangkap di Tasikmalaya karena diduga sebagai calon pengantin bom bunuh diri. Pada penghujung tahun 2014, Dodi Kuncoro juga ditangkap di Solo karena terduga akan meluluhtakkan sebuah kafe. Di penghujung tahun 2013 Densus 88 berhasil menangkap tiga orang terduga teroris di Bekasi, Lamongan, dan Jakarta. Lebih jauh lagi, pada akhir 2012 Tim Gegana berhasil menjinakkan bom di pos Polisi Poso. Situasi ini menjadi alasan kita untuk tidak tutup mata, bahwa dari waktu ke waktu aksi teror di negeri ini tidak akan ada habisnya. Bahkan bisa diprediksi di awal tahun 2017 ini.
Semakin Gencar
Berkaca pada perayaan Natal dan malam tahun baru kemarin, memang aksi kelompok teror bisa sedikit diredam oleh Polri dan TNI dan semua elemen masyarakat yang terlibat. Tidak ada laporan tentang aksi teror. Akan tetapi mereka tidak akan tinggal diam, dan bisa dipastikan kembali akan melakukan amaliyahnya (teror) pada awal tahun ini.
Kalau dikaji ulang, memang potensi ancaman teror di negeri ini dari tahun ke tahun kian meningkat. Sel-sel ISIS, Al-Qaeda dan kelompok teror lainnya kian menjamur setelah konsentrasi sentral mereka di Irak dan Suriah akhir-akhir ini dibom-bardir. Bahkan menurut sebagian pakar politik internasional konsentrasi kelompok-kelompok teror akan banting setir ke timur, wilayah ASIA, bahkan Asia Tenggara.
Setelah Aleppo dan Mosul berhasil direbut oleh meliter Iraq dan Militer Suriah di bawah komando Bashar al-Assad, pasukan ISIS kian terkepung dan jumlah mereka semakin sedikit. Apakah ini kabar baik? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena efek turunannya seperti dilema dua sisi mata uang, pada satu sisi kantong ISIS sudah hancur (kabar baik) dan pada sisi lainnya akan jadi bom waktu (kabar buruk). Karena mereka akan diaspora ke tempat-tempat lain, dengan misi pemberangusan tentu semakin intensif memerintahkan para simpatasinnya di berbagai negara untuk melakukan serangan teror.
Bisa dilihat ketika tiga serangan di Negeri Kebab (Turki) oleh kelompok teroris di penghujung taun 2016. Pertama, ketika terjadi dua pengoboman dalam waktu hampir bersamaan (10/12/16). Teror itu menyebabkan 29 orang tewas dan 166 terluka di luar stadion sepak bola Istambul, Turki. Kedua, seminggu berikutnya terjadi pembunuhan Duta Besar Rusia untuk Turki, Andrey Karlov (19/12/16). Bahkan, pada hari yang sama, pasar Natal di Breitscheidplatz, Berlin, Jerman, juga mendapatkan serangan mematikan. Sebuah truk sengaja di tabrakkan ke kerumunan warga yang menewaskan 12 orang serta melukai 49 orang lainnya.
Pada purnama yang sama, tanggal 22 Desember 2016, kelompok teroris kemudian menarasikan amarahnya dengan merilis penyiksaan terhadap dua tentara Turki yang dibakar hidup-hidup. Tragedi itu ditujukan untuk pemerintah Turki dan secara mondial mengabarkan kepada dunia bahwa mereka masih hidup gagah berani.
Dalam konteks Negara Indonesia, satu hal yang sangat disesalkan ketika membaca laporan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, bahwa; saat ini ada sekitar 2.000-an warga negara Indonesia di Suriah. Sebagian besar dari jumlah tersebut tidak terdaftar, baik keberangkatannya atau pun sesampainya di Suriah. Dari jumlah itu, Polri mencatat bahwa tidak kurang dari 500 WNI sudah bergabung dengan ISIS sampai Oktober 2016.
Jangan Lengah
Aksi teror kapan saja bisa datang di negeri ini. Kewaspadaan dan jangan lengah begitu berarti ketika negeri ini akhir-akhir ini terus dilanda perpecahan.
Kalau melihat usaha penanganan aksi teror, sejauh ini terdapat tiga model penangan terorisme di berbagai negara; yaitu war model, criminal justice system, dan internal security model. Dan ketika dicermati mayoritas negara-negara di dunia menggunakan model perang (war model), dan menggeser model penegakan hukum (criminal justice system) yang selama ini jadi opsi tunggal. Dalam model perang, Militer dan Kepolisian menjadi aktor utamanya.
Indonesia sendiri juga menggunakan pendekatan war model terhadap terorisme. Pelibatan TNI dan Polri dalam pemberantasan teroris sangat mumpuni kalau melihat track record-nya selama ini. Berbagai kalangan setuju dengan alasan memang membutuhkan TNI dan Polri untuk menindak pelaku teror.
Ancaman aksi teror memang tidak bisa diprediksi secara akurat kapan datangnya. Namun kedepannya untuk mengawali tahun 2017, selain keinginan primer kita yang sifatnya privasi, alangkah baiknya kita memasang resolusi tahun baru ini dengan “perang terhadap terorisme”.
Keluh-kesah di Padepokan Menulis
 |
| Ruangan Utama Padepokan Kutub |
Hidup di kandang panulis, atau masyhur disebut "Padepokan Kutub" sangat menyenangkan. Ada debar dan ketir yang selalu melingkupinya. Apalagi ketika di antara kami saling hujat tentang sebuah karya, dalam momentum peradilan karya, kajian sastra. Bahkan saling membenturkan argumen dalam sebuah peradilan intelektual, kajian ilmiah (dahulu: kajian tokoh). Atau pun dalam panggung suara fals kami yang kami sebut shalawat/berzanji. Atau kegiatan semi wajib, semisal piket kebersihan, iuran listrik, mengajar TPA, dll. Mengapa semi wajib, karena kami sering abai tidak bersih-bersih, nunggak bayar SPP, sampai ratusan ribu nominalnya. Atau sering absen ketika anak-anak TPA sampai-sampai menyambangi kami ke padepokan. Dari musalnya yang “wajib” akhirnya turun tahta ke “semi wajib”. Konsistensi dan istiqomah sangat langka dari keseharian kami.
Meskipun tempat kami juga dilebeli pesantren, namun kami sering main gitar, main futsal, main ketipung, main perempuan, dan tak jarang melibas waktu sakral menghadap-Nya dalam rentang waktu lima kali dalam sehari. Saya menyebutnya sebagai santri sekuler, karena segalanya bisa datang dan hidup subur di sini. Hingga pada suatu masa, ketika menjelang akhir tahun 2015, tiga laptop—kekayaan kami satu-satunya itu—sempat digondol maling jam 3 pagi, ketika kami tidur pulas dan membiarkan pintu depan menganga dengan sombongnya. Tentu kami marah, walaupun sempat ada joke-joke lucu “bangun karena ada gempa”. Selang tragedi itu, bak gayung bersambut, tulisan kami sering dimuat di media cetak koran dan majalah dan/atau website.
Saya datang ke sarang penulis ini pada Bulan Agustus 2013, pasca perayaan idul fitri, pasca ditolak oleh dua Perguruan Tinggi Yogyakarta. Tapi setelah itu, saya tancapkan “niat belajar menulis” dalam hati, dalam-dalam. Dan di dinding-dinding kayu padepokan yang insyaallah berokah ini. Waktu itu, sekira 10 santri punulis yang menyambut saya dengan ramah, santun, walaupun dibalik itu karena obyek barang bawaan saya, kardus bekas yang berisi jajanan dan beras 1 kg. Setelah itu mereka cuek banget. Ternyata memang begitu kultur penghuni padepokan ini terhadap santri baru, sengaja diuji nyali, agar mental dibangun sedini mungkin. Karena sejauh ini, saya tahu jikalau penulis-penulis di sini adalah manusia-manusia pilihan. Puluhan orang berguguran di tengah jalan, bahkan di awal perjumpaan ketika keadaan kami seperti ini.
Makin ke sini, saya mulai paham dengan lingkungan padepokan ini. Hingga pada akhirnya dipungkasi sebuah kabar baik, ketika satu semester berproses di sini, tulisan bergenre puisi dimuat di Minggu Pagi, berdempetan dengan patron saya Anwar Noeris yang sama-sama santri baru. Maka, sebagai pembuka kran itu, saya hadiahkan kepada santri penulis di sini semua honor pertama saya itu. Kalau tidak salah sekira 100 ribu rupiah. Jangan diukur dari materi kalau untuk sebuah tulisan pertama di media. cetarnya itu lhoo..
Waktu terus menggelinding, banyak melibas peristiwa, dan banyak menumbangkan para pendekar penulis di padepokan ini. Tapi jangan salah, “menumbangkan” dalam artian adalah pergi (resign) dari padepokan ini. Pendekar seangkatan saya di tahun 2013 juga tidak sedikit yang hengkang. Bukan apa-apa, bukan bangga karena berkurangnya saingan di media, tapi problem turunannya adalah siapa yang me-ngemong santri-santri anyar yang datang silih berganti.
Keluh-kesah di rumah saya ini, memang tidak untuk apa-apa. Bukan untuk kepentingan apa-apa.
Di paruh waktu tahun 2014, ketika saya semester 3 di salah satu perguruan swasta Yogyakarta, dan beberapa tulisan telah nangkring manis di media. Alangkah naifnya, alangkah tidak percayanya, saya diangkat menjadi lurah padepokan ini, dan Anwar Noeris sebagai wakilnya. Bukan apa-apa, bukan bahagia pula, tapi saya jelas-jelas menolak. Dan siapa pun diangkat jadi lurah di padepokan ini pasti menolak. Tidak ada yang legowo, terlalu pandir dengan segala macam beban yang akan dipikulnya. Walaupun tentu ada hikmah dan barokah di balik itu semua. Akhirnya saya meng-iyakan dengan desakan bertubi-tubi yang menampar di malam itu. Saya menggantikan saudara Saifa Abidillah, salah satu mahasiswa akhir UIN-SUKA, yang ketika catatan ini ditulis, masih belum juga merampungkan skripsinya.
Di awal menyandang jabatan lurah, saya tentu was-was mengambil kebijakan, karena masih ada stakeholder (empu) yang mengawasi jalannya roda padepokan agar tatap seimbang dan tidak ada ban bocor. Diantaranya, ada bapak musyawarah burung-burung Empu Ridhafi Asah Atalka, bapak kuda terbang Empu Saifa Abidillah, bapak Lawe Ahmad Naufel, dan bapak Arya Dwipangga Muafiqul Khalid MD.
Di awal jabatan ambiguitas itu, alangkah hinanya telah terjadi sedikit goresan di langit-langit padepokan ini. Yakni sebuah tragedi kemanusian, ketika salah satu dari kami berbuat sesuatu, jenaka, memalukan, dan menggoyang eksistensi padepokan ini. Amazing phenomenon. Kami mengkultusan itu sebagai “Tragedi pom bensin”, para pendekar pasti mafhum dengan istilah ini.
Di awal tahun 2015, ada pula segelintir tragedi dalam roda pemerintahan saya, yakni peristiwa ketika kami melakukan kegiatan satu malam mengenang pendiri padepokan kami Gus Zainal Arifin Thoha, haul kami menyebutnya. Tragedi itu cukup menggetarkan padepokan kami, ketika pengampu padepokan baru padepokan ini tidak mau datang ke acara itu. Kami paham, tapi toh sikap responsibility harus ditegakkan seperti selalu dikumandangkannya sesekali. Di tahun berikutnya ternyata lebih baik, karena pengampu menjadi katalisator haul, dan menjadi jimat promosi ke masyarakat bahwa sebentar lagi akan ada pembangunan padepokan baru. Di tanah sendiri samping musholla, dan tentu lebih representatif untuk dikata pesantren.
Alhamdulillah saat catatan ini ditulis, pembangunan padepokan baru kami kurang lebih telah berjalan 80%. Dengan berbagai tragedi melingkupinya, meskipun tidak maksimal 100% kami sejatinya juga terlibat dalam pembangunan, meskipun cuma angkut pasir, ngontrol kehadiran tukang, ngedak (ngecor) dll, semoga tidak dianggap tidak bantu-bantu sama sekali.
Di tahun 2016, selain kami mengardip tulisan yang dimuat dalam bentuk print out, kami juga mengarsip tulisan dalam sebuah website: lesehansastrakutubyogyakarta.blogspot.co.id/ jika antum-antum ingin mengkroscek jerih-payah kami dalam berkarya.
Pada pertengatahan tahun 2017 adalah puncak jabatan berat ini. Semoga di pundak lurah baru dan padepokan baru akan melahirkan pendekar-pendekar penulis baru. Amin...!!
Selasa, 03 Januari 2017
Tak Ada Tahun Baru Hari Ini
 |
| Add caption |
Tak ada tahun baru hari ini, tak ada tahun baru kemarin, semua tahun sama berguguran bersama air mata. Barangkali nomenklatur ini yang mewakili ketidaksanggupan kau dan aku melihat gerak-gerik manusia yang berbondong-bondong membanjiri jalanan, alun-alun, monumen, dan pantai untuk menyambut datangnya tahun baru.
Setiap tahun, kau dan aku selalu mempunyai jadwal khusus untuk menyambut malam pergantian tahun. Entah dengan pacar, teman, keluarga, atau selingkuhan, semuanya seolah-olah berada dalam arus gelombang yang memaksa kau dan aku lekas menciumi pesisir pantai. Atau antara kau dan aku seolah saling mimikri, tentang lelaku apa diantara kita masing-masing kerjakan di malam pergantian tahun. Kau meniup terompet maka aku pun juga demikian. Aku menyalakan kembang api, maka kau juga harus menyakalan kembang api. Semuanya menjadi satu rasa, satu jiwa yang memuncak dalam keramaian kota.
Tidak hanya di kota, tidak hanya di desa, dan dimanapun ada. Kau dan aku memang sengaja meluangkan waktu untuk menyambut malam pergantian tahun yang kita yakini bertuah itu. Kau dan aku menyingkirkan fokus pikiran yang selama ini membayangi kita; ambil contoh kasus bom bunuh diri dan terorisme, LGBT, reshuffle Kabinet, banjir, korupsi, pembakaran tempat ibadah, aksi demonstrasi 411 dan 212, pesona kopi Jesicca, bahkan berita nahas kegalaan Timnas Garuda mengangkat Piala AFF untuk yang kelima kalinya.
Pergantian tahun tentu harus dimaknai subtil, eksklusif, dan penuh bunga-bunga. Ada yang datang dan pergi (selamat datang Januari/selamat tinggal Desember). Tapi waktu bukanlah irisan roti yang berdempetan tapi terpisah. Karena waktu adalah serupa benang yang terus tersambung dari ujung ke pangkal. Tahun 2016 bergeser ke belakang (bukan hilang), dan digantikan oleh hari-hari di tahun 2017. Begitulah selamanya seiring irama kehidupan masih mengalun merdu.
Memang kau dan aku yang kadung kepincut untuk merakayakan tahun baru akan merasa ada yang kurang kalau tidak melakukannya kembali. Tapi kau dan aku coba pahami baik-baik nasehat lama ini: “waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Tapi, apabila sudah terlewat, maka jangan khawatir, karena waktu terbaik menanam pohon itu adalah sekarang”.
Dan waktu pula yang menciptakan ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan siapa pun yang mampu memahami waktu itulah yang akan menjadi “jawara”. Karena waktu terbuka bagi siapapun untuk dipahami. Sayang, kau dan aku sering melewatkannya begitu saja tanpa menjadikannya apa-apa. Ini barangkali yang jadi alasan metafisis dalam ajaran Islam, Tuhan banyak bersumpah menggunakan diksi yang berdimensi waktu. Sebut saja: demi masa (wal ashri), demi malam (wal laili), demi siang (wan nahari), demi fajar (wal fajri), demi bulan (wal qamari), demi matahari (wasy syamsi), demi waktu duha (wadh dhuha).
Barangkali kau dan aku akan sedikit merasa tertusuk-tusuk untuk tidak melakukan lelaku mubazir di malam pergantian tahun ketika membaca sajak Nota Bulan Desember karya Penyair Ahmad Nurullah: Tak perlu kuucapkan “selamat tinggal” pada detik terakhir bulan Desember / dan “selamat datang” untuk detik awal Januari / Untuk apa? Segala waktu sama / Waktu adalah sumbu semua sejarah, ibu segala kepedihan. Almanak pun jatuh. Telungkup. Tahun bersalin / Tapi, di antara detik-detik yang gugur, bulan-bulan membusuk / hari-hari berkarat, dan jam yang menguning, banyak hal yang masih lengket—berkecamuk dalam kenangan.
Lalu apa yang baru dari waktu? Apa yang hendak kita rayakan pada tahun baru?. Dengan nada dan getar yang sama, atau bahkan lebih lirih lagi Nurullah kembali membatin: Seperti waktu, akupun terus berjalan: gelisah oleh tatapan / mata bulan. Gemetar di bawah kerling matahari / sebab, gara-gara waktu, banyak hal berdesak untuk diingat / dan aku berjuang untuk lupa—sebagai jalan / pembebasanku.
Syahdan, ketika kau dan aku renungkan ulang memang untuk apa meluangkan waktu di malam pergantian tahun, segala waktu sama. Tapi kau dan aku mengesampingkan itu, laksana waktu yang begitu egonya menggelinding tiada henti. Kadang kau dan aku sengaja duduk berdua dengan pasangan kita masing-masing, di pojok kesunyian dan dibawah rindang cemara pantai. Atau kau dan aku swafoto dengan pasangan kita masing-masing di tengah keramaian dan dibawah binar-binar langit yang dibercaki kembang api. Untuk apa? Untuk apa?.
Barangkali kau dan aku perlu memaknai malam pergantian tahun dengan lebih santun, atau kau dan aku eloknya merenungi segala kejadian yang sudah-sudah, untuk mengawali hari-hari yang yang lebih cerah besok-besok. Atau kau dan aku renungkan sajak Selamat Tahun Baru gubahan Mustofa Bisri; Selamat tahun baru kawan / kawan, sudah tahun baru lagi / belum juga tibakah saatnya kita menunduk? / memandang diri sendiri? / bercermin firman Tuhan sebelum kita dihisabnya?.
Lebih dalam lagi Mustofa bisri mempertegas kedirian kita dalam keberagamaan kita; kawan, siapakah kita ini sebenarnya? / Muslimkah? Mukminin? Muttaqin? Khalifah Allah? Umat Muhammad-kah kita? Khairi ummatin kah kita? Atau kita sama saja dengan makhluk lain? Atau bahkan lebih rendah lagi? Hanya budak-budak perut dan kelamin.
Maka diujung tahun ini, dengan tanpa niatan menyakiti penyuka gemerlap malam pergantian tahun. Alangkah etis dan beradabnya kita menyerobot kopi ditemani sebungkos rokok saja di rumah, atau duduk di kursi goyang sambil mendengarkan lagu Auld Lang Syne karya Robert Burns (penyair Skotlandia), yang liriknya berkisah tentang persahabatan, persaudaraan, dan menyiratkan pentingnya mengenang dan merenungkan peristiwa yang sudah-sudah.
Lamunan Nostalgik
 |
| Pesantren Darul Ihsan Sumenep |
Sebagai sebuah paguyupan ilmu, Pondok Pesantren Darul Ihsan telah mencetak santri-santri penuh wawasan, religius, intelek, dan tentu diterima di masyarakat dengan baik. Dari awal berdiri hingga sekarang Pesantren Darul Ihsan menjadi barometer dan magnet untuk kawasan desa sekitar, kecamatan, bahkan kabupaten. Ini dibuktikan ketika banyak santri-santri militan yang banyak memenangkan event-event perlombaan di berbagai tingkatan, lomba pramuka misalnya.
Mengingat Darul Ihsan, tentu mengingat kedirian saya yang dimulai dari Pesantren ini. Mulai dari TK, MI, MTs, hingga MA, saya habiskan di pesantren tercinta ini. Selain karena saya juga berasal dari daerah yang sama, tentu tidak bisa dielakkan kalau pesantren ini memang posisinya di halaman rumah saya, yang sesekali senda gurau para santri, atau suara shawalatan terdengar ke bilik kamar saya. Yah, Darul Ihsan memang is the best.
Satu hal yang menjadi pijakan saya ketika di luar, yang saya dapat dari salah seorang ustad muda di pesantren ini mengatakan; “mon bedeh e dhisana oreng, sengak jhek her-beleheren, ben kengaeh oreng toanah, jhek mole mon kik tak sukses”. Maaf jimat ini tidak bisa di-translate ke bahasa Indonesia. Nah, pesan ini yang selalu menampar saya untuk tetap berdiri walau kadang angin pantai itu tiba-tiba jadi beliung.
Dalam beberapa menu kegiatan di Pesantren Darul Ihsan sangat konpleks, mulai dari kegiatan keagamaan, intelektual, kegiatan ekstra-kurikuler, pramuka, dan tentu kegiatan tahunan menyambut bulan maulid nabi, Lomba Pentas Ekspresi (LPE). Saya yakini kalau kegiatan perlombaan macam ini adalah baik untuk menunjang kreativitas, berani tampil, penuh persaingan, dan penggemblengan hidup. Namun, akhir-akhir ini ketika saya pantau dari berbagai sumber, ketika LPE dimulai sering terjadi lelaku kurang etis di antara kontestan. Sampai ada kelompok-kelompok militan yang berani menghasut santri-santri lain untuk juga larut dalam kebencian. Sehingga apa yang terjadi, akan ada gap atau jurang pemisah antara kompetitor yang mewakili kelasnya masing-masing.
Dalam kompetisi itu memang biasa terjadi, pilkades, pilkada, atau event olahraga Sea Games misalnya. Tapi sangat disayangkan kalau ini dimulai dari bawah (peantren, misalkan) sehingga efeknya akan menjamur ke adik-adik kita kelak. Apalagi menggunakan cara tidak waja.
Yah.. begitulah hidup, kita memang selalu berkompetisi dengan siapa pun dan kapan pun. Tapi ingat, kita harus profesional, kedepankan sportifitas, dan keep and touch (jaga komunikasi).
Mengenai Saya
Popular Posts
-
Google.com Sang Comandante Fidel Alejandro Castro Ruz, telah meninggal dunia pada jumat (25/11) pukul 10:30 malam waktu setempat. Kuba ...
-
Masih lekat dalam ingatan saya ketika mengikuti dialog sirkus sastra Salihara 11 Maret 2014, waktu itu Penyair Sapardi Joko Damono d...
-
Puisi adalah sebuah karya fiksi yang begitu mistik untuk dicerna, bahasanya yang puitik, kata-katanya yang efektif, dan pengandaiann...